I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Masalah.
Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya
otonomi daerah.
Prinsip otonomi daerah menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan
pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip
bahwa
untuk menangani urusan
pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kakhasan daerah.
Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud
dengan otonomi yang bertanggung jawab
adalah otonomi yang dalam
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang
pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan
bagian utama dari tujuan nasional
(Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: 167).
Untuk menyelenggarakan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan
menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara
propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan
prasyarat dalam sistem pemerintah
daerah (Bratakusumah dan Solihin,
2001: 169).
Fenomena yang muncul pada pelaksanaan
otonomi daerah dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan
pemerintah daerah yang tinggi
terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek
keuangan: Pemerintah daerah kehilangan
keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan
adanya campur tangan pemerintah
pusat yang tinggi terhadap Pemerintah daerah.
Pembangunan daerah terutama
fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara
daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan
juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan dominannya transfer dari pusat.
Adalah ironis, Kendati pelaksanaan
otonomi menitik beratkan pada kabupaten/kota sebagai ujung tombak, namun
justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi (Mudrajad Kuncoro, 2004:
18).
Setidaknya ada empat penyebab utama tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pusat
(Mudrajad Kuncoro, 2004: 13), yaitu:
1.
Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2.
Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit
yang bisa diandalkan sebagai sumber
penerimaan.
4. Ada yang khawatir bila daerah mempunyai
sumber keuangan yang tinggi
akan mendorong terjadinya
disintegrasi dan Separatisme.
Oleh karena itu, alternatif
solusi
yang
ditawarkan
adalah
(Mudrajad
Kuncoro, 2004: 15):
1. Meningkatkan
peran BUMD.
2.
Meningkatkan penerimaan
daerah.
3.
Meningkatkan pinjaman daerah.
Dari alternatif-alternatif
tersebut, pinjaman daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai
karakteristik berbeda, namun
penggunaan pinjaman sebagai alternatif
untuk mengurangi ketergantungan
fiskal dapat dipertanggungjawabkan sepanjang memenuhi
berbagai persyaratan seperti adanya kemampuan membayar kembali serta pemanfaatan yang berguna bagi pelayanan masyarakat atau pembangunan
daerah.
Dalam penjelasan umum
yang tertuang dalam peraturan pemerintah
nomor 107 tahun 2000, ditegaskan
bahwa: dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan
daerah, pemerintah pusat memberikan
peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman. Namun demikian,
pinjaman daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) (Yook Tri
Handoko, 2003: 3).
Dalam masalah keuangan daerah,
perimbangan pembiayaan pemerintah
pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri
masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer
pusat.
Pemerintah Daerah selama
ini memiliki keterbatasan pembiayaan
dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen
pembiayaan terbesar berasal dari dana
transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD,
potensi
pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman
daerah (Rokhedi P. Santoso, 2003: 148).
Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan
pembangunan memiliki
keuntungan, antara lain
dapat mengatasi
keterbatasan kemampuan riil
atau nyata pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan
memiliki
kapasitas fiskal yang memadai.
Dengan pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan
masyarakat dan pembangunan
daerah-daerah.yang dimaksud. Jenis pinjaman
ini
merupakan pinjaman
jangka
panjang.
Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk mem-biayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang pinjaman
jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi
umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.
Untuk mengurangi ketergantungan daerah
kapada pusat, pinjaman jangka panjang
dianggap lebih efektif
daripada pinjaman jangka pendek
(Rokhedi P. Santoso, 2003: 148).
Berdasarkan pemikiran tersebut,
maka dalam rangka penyusunan skripsi dipilih judul Analisis
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten
Lampung
Utara Tahun 2010
1.2. Identifikasi
Masalah
Berdasarkan uraian tentang
latar belakang masalah diatas, dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Rendahnya
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara
2. Tingginya
Ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap Pemerintah Pusat.
3. Rendahnya
Pendapatan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah.
1.3.
Permasalahan
Dari uraian identifikasi
masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai
berikut : “Seberapa besar Derajat
Desentralisasi Fiskal
Keuangan Daerah serta Bagaimana Kapasitas Pinjaman Daerah
Kabupaten Lampung Utara yang
dihitung dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR)?
1.4. Tujuan
Penelitian.
1.
Untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah sehingga bisa diketahui rasio
penerimaan daerah yang paling menonjol terhadap Total Penerimaan Daerah.
2. Untuk mengukur kapasitas
Pinjaman Daerah sebagai
alternatif untuk mengurangi
ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang
strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan
di STIE Ratula Kotabumi
4. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan pemerintah
daerah dan lembaga-lambaga terkait di Kabupaten Lampung Utara.
1.5.
Kerangka
Pemikiran
Dari uraian-uraian diatas maka
terbentuklah suatu kerangka pemikiran yang dapat penulis gambarkan sebagai
berikut :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
1.6.
Metode
Penelitian
Bardasarkan pada
tujuan penelitian maka bentuk
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu memusatkan
pada suatu kasus tertentu secara intensif, dalam hal
ini adalah analisis
keuangan daerah dan perhitungan kemampuan kabupaten dalam melakukan pinjaman daerah.
Jenis dan Metode Pengumpulan Data.
Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif. Yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Lampung Utara berupa laporan tahunan yang bersangkutan.
Data yang dipergunakan Pendapatan
Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
Bantuan, Sumbangan Subsidi, Dana
Alokasi Umum, Belanja
Wajib atau Belanja Rutin, Pinjaman dan Bunga yang Jatuh Tempo dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-
lain.
Batasan Variabel.
Supaya tidak terjadi
salah penafsiran terhadap
suatu variabel maka dalam penelitian ini dibuat
batasan-batasan variabel yang digunakan sebagai berikut:
1. Derajat
desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara nilai pendapatan asli
daerah (PAD), yang meliputi hasil
pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah seperti
laba Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan
dari dinas-dinas, dan penerimaan
lain-lain yang sah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah), bagi hasil
pajak dan bukan pajak (BHPBP, bagi hasil pajak misalnya Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak Penghasilan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan, sedang
bagi hasil bukan pajak seperti penerimaan
kehutanan, penerimaan pertambangan, penerimaan perikanan, penerimaan
pertambangan minyak) dan sumbangan
(SB, yang meliputi Sumbangan dan Bantuan (sebelum otonomi daerah) dan Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus (sesudah otonomi daerah)) terhadap total penerimaan daerah (TPD,
Total Penerimaan Daerah meliputi Sisa
Lebih Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana
Perimbangan yang meliputi bagi Hasil Pajak
dan
Bukan
Pajak,
Dana
Alokasi
Umum,
dana
Alokasi Khusus, dan Bagian Penerimaan
Pembangunan yang meliputi penerimaan dari pemerintah
pusat, pinjaman pemerintah daerah, pinjaman untuk BUMD.
2. Pinjaman Daerah untuk mengurangi
ketergantungan terhadap pemerintah
pusat dihitung dengan menggunakan
rumus pinjaman daerah jangka panjang, karena pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup
kekurangan arus kas sedangkan pinjaman
jangka menengah dipergunakan untuk
membiayai
penyediaan
pelayaan
umum
yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Besarnya
jumlah
Sisa
Pokok
Pinjaman dihitung dengan menjumlahkan
sisa Pinjaman Daerah dengan jumlah pinjaman
yang akan ditarik tidak melebihi
75% dari jumlah penerimaan umum
APBD tahun sebelumnya. Penerimaan APBD sebelumya adalah seluruh penerimaan
APBD tidak termasuk Dana Alokasi
Khusus (sebelum tahun 2001 atau sebelum
berlakunya otonomi daerah, Dana Alokasi Khusus menggunakan nama Bantuan),
Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan
penerimaan lain
yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran
tertentu.
4. Besarnya
pinjaman daerah jangka panjang
yang
dihitung
dengan
rumus Debt Service Coverage
Ratio (DSCR) dihitung dengan menjumlahkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (sebelum tahun 2001 atau sebelum berlakunya
otonomi daerah , Dana Alokasi Umum menggunakan nama Sumbangan),
dan Bagian Daerah dikurangi Belanja Wajib dibagi
Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga Pinjaman, dan Biaya Lain, dimana jumlahnya lebih besar dari 2,5.
1.7.
Alat
Analisis
Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan alat analisa deskriptif. Analisa deskriptif
dimaksudkan untuk memberi gambaran perkembangan
Derajat Desentralisasi Fiskal
dan perkembangan realisasi Pinjaman Daerah yang sudah dilakukan, dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:
1. Analisis
Derajat Desentralisasi Fiskal.
Metode
analisis ini digunakan untuk menganalisis
hubungan antara keuangan pusat-daerah dan kemandirian
pembiayaan keuangan daerah, dalam hal
ini desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan
daerah. Analisis ini menggunakan metode rasio,
yaitu membandingkan antara nilai :
a)
PAD
Keterangan: PAD : Pendapatan Asli Daerah.
TPD :
Total Penerimaan Dearah.
b)
BHPBP
Keterangan: BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TPD :
Total Penerimaan Dearah.
c)
SB
Keterangan: SB : Sumbangan dan Bantuan.
TPD : Total Penerimaan
Dearah
(Tri Nurmani Ariyanti, 2002, 10)
Berdasarkan rasio ketiga komponen tersebut dalam
struktur penerimaan APBD akan diketahui derajat desentralisasi fiskal daerah;
(Tri Nurmani Ariyanti, 2002: 10);
·
Derajat desentralisasi fiskal rendah bila
kontribusi pos sumbangan dan bantuan
terhadap total penerimaan daerah
lebih besar dari kontribusi pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak dan
bukan pajak terhadap total penerimaan
daerah yang berarti keuangan daerah masih
tergantung pada pemerintah pusat.
·
Derajat desentralisasi fiskal tinggi jika
kontribusi pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap
total penerimaan daerah lebih besar dari kontribusi bantuan dan sumbangan terhadap total penerimaan daerah yang berarti keuangan daerah
dikatakan mandiri
2.
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang Daerah yang dapat diperoleh.
a. Jumlah
Sisa Pokok Pinjaman.
Dalam UU no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah, salah satu syarat yang harus
dipenuhi oleh daerah dalam melakukan
pinjaman daerah adalah dengan Jumlah
Sisa Pokok Pinjaman. Yaitu
Jumlah Sisa Pokok
Pinjaman ditambah jumlah
pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, atau:
SPP + Pt
< 75%.TPn-1
Keterangan:
SPP : Jumlah Sisa Pokok Pinjaman.
Pt : Jumlah
Pinjaman yang akan ditarik.
TPn-1 : Jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
Penerimaan Umum yaitu seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi
Khusus (sebelum tahun 2001 atau sebelum berlakunya otonomi daerah,
Dana Alokasi Khusus menggunakan nama
Bantuan), Dana Darurat, dana pinjaman
lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai
pengeluaran tertentu.
Suatu daerah jika jumlah sisa pokok pinjamannya ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (<75%) dari jumlah
penerimaan umum
APBD
tahun
sebelumnya maka
daerah
tersebut boleh melakukan pinjaman daerah
jangka panjang, sebaliknya jika jumlah
sisa pokok pinjamannya ditambah jumlah
pinjaman yang akan ditarik melebihi 75% (>75%) dari jumlah penerimaan umum
APBD tahun sebelumnya maka daerah tersebut tidak boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang.
b. Debt
Service Coverage Ratio (DSCR)
Besarnya pinjaman jangka panjang yang dapat diperoleh
kabupaten dapat dicari dengan rumus (Penjelasan UU No. 33 tahun 2004 pasal
54 Huruf b):
(PAD + DAU +
(DBH − DBHDR) − BW
P + B + BL
Keterangan:
DSCR : Debt
Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan
Membayar Kembali Pinjaman.
PAD : Pendapatan
Asli Daerah.
DAU : Dana Alokasi Umum.
DBH : Dana Bagi Hasil.
DBHDR : Dana Bagi Hasil dana
Reboisasi.
BW :
Belanja Wajib, yaitu belanja
yang harus dipenuhi
atau tidak bisa dihindarkan
dalam tahun anggaran yang bersangkutan
oleh Pemerintah Daerah seperti
Belanja Pegawai.
P : Angsuran
pokok
pinjaman yang jatuh tempo
pada
tahun
anggaran yang bersangkutan.
B : Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran
yang bersangkutan.
BL : Biaya Lain (biaya komitmen, biaya bank, dam lain-lain)
yang jatuh tempo.
Secara Umum DSCR merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan
untuk suatu pinjaman. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia No. 107 tahun 2000
Tentang Pinjaman Daerah mengenai
Persyaratan Pinjaman Daerah,
nilai dari DSCR paling sedikit 2,5 (dua setengah),
jadi bila nilai DSCR suatu daerah lebih besar atau sama
dengan
2,5
( ≥ 2,5 )
maka daerah boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang, sebaliknya jika nilai DSCR suatu daerah
lebih
kecil
dari
2,5
( ≤ 2,5 )
maka daerah tidak boleh
melakukan pinjaman daerah jangka panjang.
1.8. Sistematika
penulisan.
Skripsi ini dibagi menjadi
5 bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, alat
analisis dan sistematika penulisan.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini
berisi empat bagian; pertama tentang
landasan teori yang berisikan teori Otonomi Daerah, kedua berisi Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, ketiga berisi tentang
Desentralisasi Fiskal Daerah, Keempat
berisi tentang Pinjaman Daerah.
BAB III. GAMBARAN
UMUM
Bab ini merupakan uraian atau gambaran
atau deskripsi secara umum tentang Kabupaten
Lampung Utara.
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi uraian dan hasil analisa dan
pengolahan data.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi dua bagian;
pertama merupakan kesimpulan
yang diperoleh dari hasil analisis; kedua merupakan
saran sebagai jawaban dari rumusan masalah.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah dan Solihin
(2002),
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Elmi, Bachrul (2002),
Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI-
Pres, Yogyakarta.
Kuncoro,
Mudrajad
(2004),
Otonomi & Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.
Suparmoko
(2002), Ekonomi Publik
Untuk
Keuangan dan
Pembangunan Daerah, ANDI,
Yogyakarta.
UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
beserta Penjelasannya, Citra Umbara,
Bandung.
Ariyanti, Tri Nurmani
(2002),
Analisis Kesiapan Keuangan Daerah
Dalam Rangka Otonomi Daerah
di Kabupaten Klaten
Tahun 1989/1990-1999-2000, Fakultas
Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Handoko,
Yook Tri (2003), Kemampuan Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan
Pinjaman Sebagai Alternatif
Pembiayaan Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran”, Yogyakarta.
Santoso, Rokhedi
P. (2003) “Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Volume VIII, No. 2, 147-158.

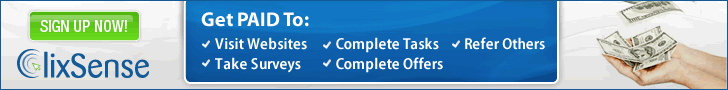

Tidak ada komentar:
Posting Komentar